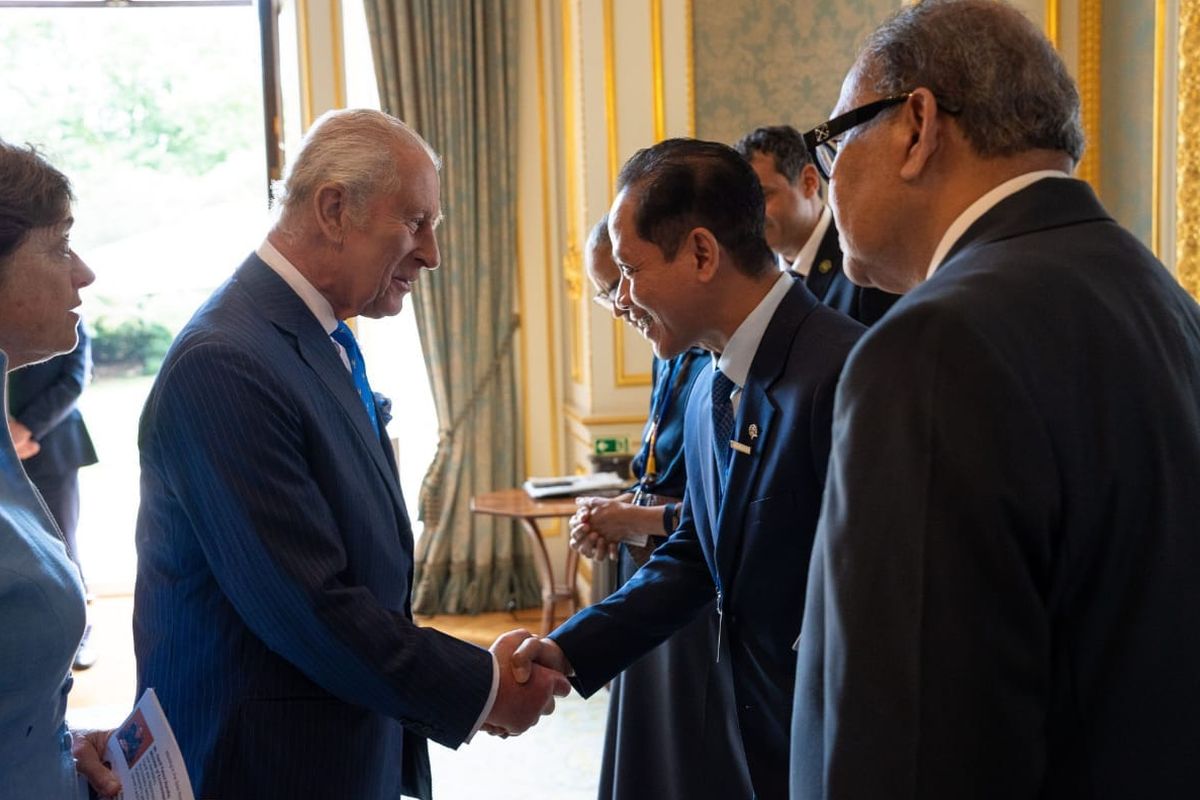Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan spesies laut dilindungi di Indonesia.
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Sarmintohadi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan RAN sebagai panduan strategi perlindungan dan pengelolaan penyu serta cetacea.
Ia menyoroti bahwa kedua spesies ini memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang tinggi, terutama bagi masyarakat pesisir.
“Penyusunan rencana aksi ini adalah langkah konkret untuk mendorong perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan,” ujar Sarmintohadi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis KKP Rabu (2/7/2025).
Proses penyusunan RAN ini diinisiasi KKP bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, peneliti BRIN, sejarawan, hingga organisasi masyarakat sipil.
Beberapa rekomendasi strategi yang dibahas meliputi pembentukan pusat konservasi penyu (Center of Excellence) di tiga lokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan mamalia laut terdampar, serta penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir terhadap cetacea.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, berharap dokumen RAN ini tidak berhenti pada perencanaan, tapi benar-benar menjadi acuan bersama untuk perlindungan nyata di lapangan.
Ranny R. Yuneni dari Yayasan WWF Indonesia menekankan bahwa konservasi berbasis data dan sains mutakhir menjadi kunci efektivitas perlindungan, terutama untuk habitat, kelembagaan lokal, dan pemanfaatan teknologi guna memitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan cetacea.
Dalam forum ini, sejumlah isu krusial turut dibahas, mulai dari kondisi terkini spesies, tantangan pengelolaan habitat penting, hingga arah kebijakan di tengah tekanan aktivitas manusia dan krisis iklim. Salah satu sesi penting adalah pembahasan dokumen matriks aksi, yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas, dan penanggung jawab pelaksana.
Dari perspektif lokal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menekankan bahwa pendekatan spiritual dan budaya juga berperan penting. Ia menyebut ajaran Segara Kerthi dalam Sad Kerthi sebagai nilai lokal yang mendorong pelestarian laut sebagai bagian dari keseimbangan hidup.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk merampungkan dokumen RAN dan menyusun strategi implementasi di wilayah prioritas. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan bersama bagi berbagai pihak dalam perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa komitmen konservasi spesies laut sejalan dengan prinsip ekonomi biru, yang menyeimbangkan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.